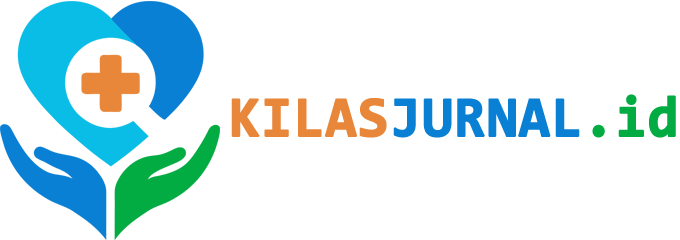Mitos: Orang Jawa dan Sunda Tak Boleh Menikah
Selama berabad-abad, sebagian masyarakat di Jawa Barat dan Jawa Tengah mempercayai bahwa orang Jawa dan orang Sunda tidak sebaiknya menikah.
Katanya, hubungan dua suku besar ini akan berakhir buruk — entah rumah tangga tak langgeng, rezeki seret, atau keluarga saling bertentangan.
Larangan ini sering disampaikan secara halus oleh orang tua:
“Jangan kawin sama orang Sunda, nanti nasibmu sial.”
“Orang Jawa itu beda watak, nanti ribut terus.”
Mitos ini terus diwariskan lintas generasi, bahkan masih terdengar di era modern. Tapi dari mana asalnya?
Fakta: Akar Sejarahnya dari Peristiwa Bubat
Larangan menikah antara orang Jawa dan Sunda berakar dari Tragedi Bubat (1357 M), peristiwa yang terjadi di masa Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda Pajajaran.
Kisah ini tertulis dalam naskah Pararaton dan Kidung Sunda.
Kala itu, Dyah Pitaloka Citraresmi, putri Raja Sunda, hendak menikah dengan Hayam Wuruk, Raja Majapahit.
Namun, Mahapatih Gajah Mada menganggap kedatangan rombongan Sunda sebagai bentuk penyerahan diri — bukan lamaran pernikahan setara.
Kesalahpahaman itu memicu pertumpahan darah di Bubat.
Raja Sunda dan seluruh pengiringnya tewas, termasuk Sang Putri yang bunuh diri demi menjaga kehormatan.
Sejak saat itu, hubungan politik dan budaya antara dua kerajaan besar itu retak dalam-dalam.
Legenda menyebut rakyat Sunda menyimpan luka, dan masyarakat Jawa merasa malu.
Dari trauma itulah muncul kepercayaan bahwa “Jawa dan Sunda tidak cocok bersatu.”
“Bubat bukan hanya peristiwa politik, tapi luka batin dua bangsa serumpun,”
jelas Dr. Pudentia MPSS, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Indonesia (ATL).
“Mitos pernikahan itu lahir dari memori kolektif yang belum selesai.”
Mitos yang Berevolusi Jadi Stereotip Sosial
Seiring waktu, trauma sejarah itu berubah menjadi prasangka sosial.
Masyarakat Sunda menilai orang Jawa “terlalu halus dan licik,”
sementara masyarakat Jawa menganggap orang Sunda “terlalu keras kepala.”
Padahal, sifat-sifat itu bukan kodrat suku, melainkan hasil stereotip turun-temurun yang dikuatkan lewat cerita rakyat dan nasihat keluarga.
Mitos pernikahan pun berkembang jadi tabu budaya — bukan aturan tertulis, tapi aturan emosional yang dipegang banyak keluarga.
“Ini bukan larangan hukum, tapi tabu moral yang diwariskan,” kata Dr. Ayu Sutarto, antropolog Universitas Jember.
“Masalahnya, tabu itu sering dipelihara tanpa lagi mengingat konteks sejarahnya.”
Fakta: Tak Ada Larangan dalam Agama atau Hukum
Dari sisi agama, hukum, maupun adat nasional, tidak ada satu pun aturan yang melarang pernikahan antara orang Jawa dan Sunda.
Negara hanya mengatur syarat umum perkawinan: umur, persetujuan, dan kesesuaian agama.
Bahkan dalam ajaran Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha — yang banyak dianut di Jawa dan Sunda — perbedaan etnis sama sekali bukan penghalang.
Yang ditekankan justru kesetiaan, tanggung jawab, dan keharmonisan rumah tangga.
Jadi, jika ada yang masih menolak pernikahan lintas suku, alasan itu lebih bersifat sosial-budaya, bukan spiritual atau hukum.
Bukti Nyata: Banyak Pasangan Jawa–Sunda yang Harmonis
Di masa modern, banyak contoh pernikahan Jawa–Sunda yang berhasil dan bahagia.
Mulai dari tokoh publik, seniman, hingga masyarakat biasa.
Misalnya, alm. Didi Kempot (Jawa) yang menikah dengan Yan Vellia (Sunda),
atau pasangan Ariel NOAH (Sunda) dengan Sophia Latjuba (berdarah campuran, Jawa–Jerman).
Ratusan ribu keluarga di Jawa Barat dan Jawa Tengah kini hidup berdampingan tanpa konflik budaya.
Di banyak daerah perbatasan seperti Cirebon, Brebes, dan Banyumas, identitas “Jawa–Sunda” justru melebur alami — bahasa, makanan, dan adat sudah saling memengaruhi.
“Yang penting komunikasi dan saling menghormati,” ujar Dewi Rahayu (36), perempuan Sunda yang sudah 10 tahun menikah dengan pria Jawa.
“Kita malah jadi belajar dua budaya sekaligus.”
Kenapa Mitos Ini Masih Bertahan?
Menurut penelitian Pusat Studi Budaya Universitas Padjadjaran (2022),
mitos larangan Jawa–Sunda tetap hidup karena fungsi sosialnya berubah.
Dulu, ia menjaga batas identitas setelah konflik. Sekarang, ia jadi bentuk “humor budaya” atau permainan stereotip antar suku.
Ungkapan seperti “hati-hati kawin sama orang Sunda” atau “orang Jawa licin” sering muncul sebagai lelucon — tapi tetap memperkuat kesan jarak.
“Kalau tidak dikritisi, humor bisa melestarikan prasangka,” tulis riset itu.
“Padahal, generasi muda kini lebih cair dalam melihat perbedaan.”
Fakta: Sejarah Bisa Menyakitkan, Tapi Cinta Bisa Menyembuhkan
Konflik masa lalu memang nyata, tapi trauma bukan warisan yang wajib diteruskan.
Setiap generasi berhak menafsir ulang sejarah, bukan hidup di bawah bayangannya.
Ketika dua insan Jawa dan Sunda menikah hari ini,
mereka sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang simbolis:
menyembuhkan luka sejarah lewat cinta dan kebersamaan.
“Perkawinan lintas suku adalah bentuk rekonsiliasi budaya,” kata Dr. Pudentia.
“Sejarah tidak bisa dihapus, tapi bisa dipeluk bersama.”
Kesimpulan: Mitos Tak Harus Jadi Batas
Larangan pernikahan Jawa–Sunda hanyalah mitos budaya yang lahir dari peristiwa sejarah tragis.
Kini, konteksnya sudah berubah — Indonesia berdiri atas semangat persatuan dalam keberagaman.
Tidak ada alasan rasional, agama, atau hukum yang melarang dua orang dari suku berbeda untuk menikah.
Yang menentukan bukan asal daerah, tapi cara saling memahami dan menghormati perbedaan.
Maka, jika ada yang berkata “Jawa dan Sunda tak bisa bersatu,”
jawab saja dengan tenang:
“Mereka pernah berperang di Bubat, tapi sekarang bersatu di pelaminan.”