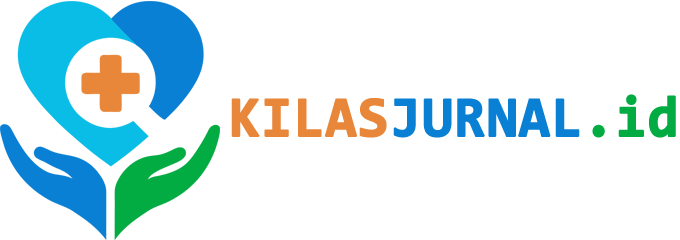Bagaimana Budaya Menentukan Apa yang Kamu Rasakan dan Apa yang Seharusnya Kamu Rasakan
JAKARTA kilasjurnal.id — Saat kita merasakan marah, sedih, atau bahagia, sering kali kita menganggap emosi itu muncul begitu saja dari dalam diri kita sebagai reaksi alami terhadap situasi. Namun menurut penelitian lintas budaya, emosi sejatinya lebih dari sekadar reaksi biologis instan; ia dipengaruhi dan dibentuk oleh budaya di mana kita hidup.
Artikel yang dirilis 13 Januari 2026 menjelaskan bahwa asumsi umum selama ini — bahwa emosi itu universal dan sama di mana pun — ternyata tidak sepenuhnya tepat. Sebaliknya, budaya membentuk tidak hanya apa yang kita rasakan, tetapi juga apa yang kita anggap seharusnya dirasakan.
Emosi Bukan Sekadar Respons Batiniah
Secara tradisional banyak orang percaya bahwa emosi adalah reaksi spontan dari otak terhadap kejadian tertentu. Namun penelitian dalam psikologi lintas budaya menegaskan bahwa emosi juga dikonstruksi oleh konteks sosial dan budaya seseorang. Itu berarti bagaimana kita memahami suasana hati, bagaimana kita menilai perasaan orang lain, dan bagaimana kita mengekspresikannya, sangat dipengaruhi oleh norma budaya.
Budaya membentuk kerangka makna yang dipakai untuk menafsirkan perasaan batin kita. Misalnya, di beberapa masyarakat, rasa malu mungkin dianggap sebagai tanda tanggung jawab sosial yang kuat, sementara di budaya lain rasa itu mungkin dipandang sebagai sesuatu yang memalukan atau negatif. Konteks sosial dan nilai moral suatu budaya menentukan apakah suatu perasaan dianggap pantas, berlebihan, atau diinginkan.
Penelitian Besar Menentang Mitos Umum tentang Budaya Emosi
Sebuah tinjauan terbaru yang dirangkum dari artikel psikologi budaya menunjukkan temuan penting: anggapan bahwa budaya individualistik memberi kebebasan emosional dan budaya kolektivistik membatasi ekspresi emosi adalah sebuah kesalahpahaman. Realitanya justru lebih kompleks.
Penelitian lintas lebih dari 60 negara mengungkap bahwa masyarakat individualistik cenderung menunjukkan keseragaman emosional yang tinggi, baik pada perasaan yang dialami maupun pada emosi yang dianggap ideal untuk dialami. Sementara itu, masyarakat kolektivistik cenderung menunjukkan diversitas emosional yang lebih besar karena emosi dinilai secara lebih kontekstual dalam kaitannya dengan hubungan sosial.
Misalnya, dalam budaya kolektivistik, ekspresi emosional yang tampak “tertahan” atau tidak terbuka bukan berarti seseorang tidak merasa sedih atau marah, tetapi bisa jadi cara yang dipakai untuk memelihara harmoni sosial dan menghormati orang lain.
Budaya Individualistik vs. Kolektivistik dalam Regulasi Emosi
Dalam budaya Barat yang cenderung individualistik, banyak model terapi dan pandangan sosial menekankan bahwa ekspresi emosional yang jujur dan terbuka adalah tanda kesehatan psikologis. Terapi sering menargetkan ekspresi bebas dan pengurangan emosi negatif.
Namun dalam budaya kolektivistik, tujuan regulasi emosi bisa berbeda. Menjaga keterhubungan atau harmoni sosial, melindungi hubungan, serta mempertahankan martabat orang lain sering menjadi nilai yang lebih tinggi daripada sekadar mengekspresikan perasaan secara bebas. Di sini, menahan emosi negatif bisa dilihat sebagai strategi sosial yang cerdas dan adaptif.
Perbedaan ini penting dipahami terutama bagi praktisi psikologi atau terapis yang bekerja dengan klien dari latar budaya yang berbeda. Kesalahan menafsirkan gaya ekspresi emosi yang dipengaruhi budaya bisa menjadi kendala dalam proses terapi atau memahami kondisi emosional orang lain.
Budaya dan “Ideal Affect”: Apa yang Harus Kita Rasakan?
Teori Affect Valuation Theory menjelaskan konsep penting dalam kajian budaya dan emosi: budaya tidak hanya mempengaruhi pengalaman emosional aktual, tetapi juga ideal affect — yakni jenis emosi yang dinilai paling diinginkan atau “seharusnya” dirasakan oleh anggota budaya tersebut.
Misalnya, di beberapa masyarakat individualistik, emosi positif yang berkaitan dengan energi tinggi seperti antusiasme dan kegembiraan sering dipandang sebagai ideal. Sebaliknya, dalam beberapa budaya Timur, keadaan emosi yang lebih tenang dan damai mungkin lebih dihargai sebagai ideal karena dianggap menunjang keseimbangan dan keharmonisan.
Ideal affect ini juga mempengaruhi perilaku sosial: orang akan secara tidak sadar mengejar atau menahan jenis perasaan tertentu karena tekanan sosial yang diinternalisasi lewat budaya.
Bahasa dan Budaya: Membentuk Perasaan melalui Kata-Kata
Bahasa yang digunakan sehari-hari juga memainkan peran besar dalam bagaimana emosi diidentifikasi dan dipahami. Teori yang dikenal sebagai Sapir-Whorf menunjukkan bahwa bahasa dapat mempengaruhi cara kita memikirkan dan memahami dunia, termasuk bagaimana kita mengkategorikan dan mengartikulasikan perasaan kita.
Sebagai contoh, beberapa budaya memiliki istilah emosional yang tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa lain. Istilah seperti “amae” dalam budaya Jepang atau “gemütlichkeit” dalam budaya Jerman dapat menjelaskan nuansa emosi yang spesifik budaya tersebut dan tidak mudah diterjemahkan atau dipahami dalam konteks lain.
Implikasi Budaya Terhadap Praktik Terapi dan Interaksi Antarbudaya
Pentingnya memahami konteks budaya juga semakin relevan di era globalisasi saat ini. Ketika orang dari latar budaya berbeda bertemu — baik dalam hubungan interpersonal, tempat kerja, atau terapi psikologis — perbedaan dalam cara memahami emosi bisa memunculkan salah tafsir.
Seorang terapis yang tidak memahami nilai budaya klien mungkin menginterpretasikan cara klien menahan emosi sebagai resistensi terhadap perubahan, padahal itu hanya cara klien tersebut menjaga relasinya atau melindungi martabat orang lain. Praktik terapi yang efektif justru menuntut cultural humility — yakni kesadaran bahwa tidak ada satu cara universal dalam memahami perasaan manusia.
Selain itu, di lingkungan kerja internasional atau hubungan lintas budaya, mengetahui bahwa budaya membentuk preferensi emosional membantu mengurangi konflik dan meningkatkan empati serta keterampilan komunikasi.
Konteks Sosial dan Budaya Emosi dalam Kehidupan Sehari-hari
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami tekanan sosial yang tidak disadari yang mempengaruhi perasaan kita tentang perasaan itu sendiri. Misalnya, seseorang bisa merasa “seharusnya bahagia” dalam suatu budaya yang menilai optimisme tinggi, sementara orang lain dalam budaya berbeda mungkin merasa bahwa menahan emosi negatif demi menjaga keharmonisan adalah hal yang baik.
Kesadaran bahwa perasaan kita dipengaruhi budaya dapat membantu kita lebih peka terhadap diri sendiri dan orang lain, terutama dalam konteks hubungan sosial atau lintas budaya. Ketika kita memahami bahwa emosinya bukan hanya “reaksi biologis belaka”, kita bisa lebih inklusif dalam menilai pengalaman perasaan orang lain dan mengurangi prasangka budaya.
Kesimpulan: Emosi sebagai Konstruksi Budaya
Penelitian lintas budaya membuka perspektif baru tentang emosi: bukan sebagai sesuatu yang universal dan netral, tetapi sebagai konstruksi yang dibentuk oleh budaya, norma sosial, dan bahasa. Karena itu:
- Emosi dipengaruhi oleh nilai budaya dan ekspektasi sosial.
- Individu dalam budaya yang berbeda dapat memiliki makna dan regulasi emosional yang berbeda atas emosi yang sama.
- Pemahaman budaya penting dalam konteks hubungan interpersonal, terapi, dan komunikasi lintas budaya.
Dengan melihat emosi sebagai hasil interaksi antara pengalaman pribadi dan konteks budaya, kita dapat memahami diri sendiri serta orang lain dengan lebih empatik dan kontekstual.