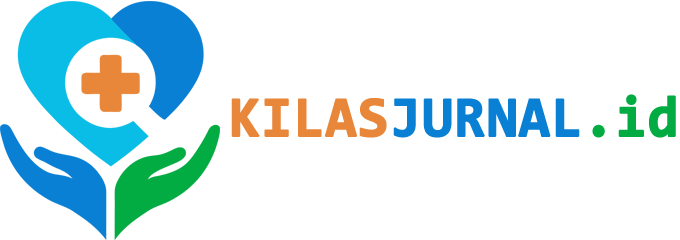Fakta vs Mitos: Benarkah Media Sosial Menjadi Penyebab Utama Stres Modern?
JAKARTA, kilasjurnal.id – Di era digital ini, rasanya hampir mustahil menemukan orang yang tidak memiliki setidaknya satu akun media sosial. Platform seperti Instagram, TikTok, dan X (Twitter) telah menjadi bagian dari ritual harian, mulai dari bangun tidur hingga kembali memejamkan mata. Namun, seiring dengan meningkatnya waktu layar (screen time), keluhan mengenai kecemasan, kelelahan mental, dan stres juga meroket. Pertanyaan besarnya: apakah adil menuduh media sosial sebagai terdakwa tunggal atau penyebab utama dari epidemi stres ini?
Untuk menjawabnya, kita perlu melihat data psikologis dan mekanisme kerja otak, memisahkan mana yang merupakan korelasi nyata dan mana yang sekadar asumsi.
Fakta: Media Sosial Adalah “Amplifier” Stres yang Kuat
Secara ilmiah, pernyataan bahwa media sosial menyebabkan stres adalah FAKTA, namun dengan catatan penting: ia seringkali bukan penyebab tunggal, melainkan amplifier (penguat) dari kerentanan mental yang sudah ada.
Penelitian dari American Psychological Association secara konsisten menunjukkan korelasi linear antara durasi penggunaan media sosial dengan tingkat kortisol (hormon stres) dalam tubuh. Mekanisme utamanya bekerja melalui apa yang disebut psikolog sebagai Social Comparison Theory atau Teori Perbandingan Sosial.
Manusia secara evolusioner memang dirancang untuk membandingkan diri dengan orang lain sebagai cara mengukur posisi sosial dalam kelompok. Masalahnya, media sosial mendistorsi proses ini. Di dunia nyata, kita membandingkan diri dengan tetangga atau rekan kerja yang kondisinya relatif setara. Di Instagram atau TikTok, otak kita dipaksa membandingkan “dapur berantakan” kita dengan “etalase kehidupan” orang lain yang telah dikurasi sempurna, diberi filter, dan disunting.
Ketimpangan persepsi inilah yang memicu perasaan tidak cukup (inadequacy), iri hati, dan rendah diri. Otak menerjemahkan perasaan “tertinggal” ini sebagai ancaman sosial, yang kemudian memicu respons fight or flight ringan namun kronis, berujung pada kelelahan mental.
Jebakan Dopamin dan Kecemasan
Selain perbandingan sosial, fitur teknis dari aplikasi itu sendiri dirancang untuk memanipulasi neurokimia otak. Fitur infinite scroll (gulir tanpa batas) dan notifikasi acak diciptakan meniru mekanisme mesin slot perjudian.
Setiap kali kita membuka aplikasi atau menarik layar untuk refresh, otak melepaskan dopamin—hormon yang berkaitan dengan antisipasi dan imbalan. Kita berharap melihat sesuatu yang menarik atau “like” baru. Namun, ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, atau ketika kita justru melihat berita buruk atau komentar negatif, level dopamin anjlok drastis. Fluktuasi neurokimia yang tajam dan berulang-ulang dalam sehari ini membuat sistem saraf menjadi hipersensitif, menyebabkan kita mudah tersinggung, cemas, dan sulit fokus.
Mitos: Semua Penggunaan Media Sosial Berdampak Buruk
Di sinilah letak mitos yang perlu diluruskan. Tidak semua interaksi di media sosial menghasilkan racun mental. Studi membedakan antara penggunaan aktif dan pasif.
Penggunaan aktif—seperti mengirim pesan ke teman, berdiskusi di komunitas hobi, atau mengunggah karya—justru bisa meningkatkan kesejahteraan mental karena memenuhi kebutuhan dasar manusia akan koneksi sosial. Sebaliknya, penggunaan pasif—hanya menggulir layar (scrolling) tanpa berinteraksi, mengintip profil orang lain (stalking), dan menyerap informasi tanpa filter—adalah jenis perilaku yang paling kuat hubungannya dengan depresi dan stres.
Jadi, menuduh media sosial sebagai “jahat” secara inheren adalah mitos. Ia hanyalah alat. Pola pemakaian pasif dan tanpa sadar (mindless scrolling) itulah yang menjadi racunnya.
Fenomena FOMO sebagai Pemicu Stres Baru
Validitas media sosial sebagai sumber stres juga dikuatkan oleh fenomena FOMO (Fear of Missing Out). Ini bukan sekadar istilah gaul, melainkan kondisi psikologis nyata di mana seseorang merasa cemas bahwa orang lain sedang mengalami hal-hal menyenangkan tanpa dirinya.
Algoritma media sosial memperparah ini dengan terus-menerus menyodorkan tren terbaru, tempat liburan terhits, atau pencapaian karier orang lain. Bagi otak manusia purba, “tertinggal dari kelompok” adalah ancaman kematian, sehingga respons stres pun aktif. Di zaman modern, ancaman itu tidak nyata, namun tubuh meresponsnya dengan gejala fisik yang sama: jantung berdebar, sulit tidur, dan gelisah.
Kesimpulan
Menyebut media sosial sebagai penyebab stres adalah fakta yang didukung data ilmiah, terutama jika dikaitkan dengan mekanisme perbandingan sosial dan manipulasi dopamin. Namun, ia tidak bekerja sendirian. Media sosial menjadi berbahaya ketika ia mengisi kekosongan jiwa, menggantikan interaksi tatap muka, dan digunakan secara pasif tanpa kontrol diri. Solusinya bukan serta-merta menghapus akun, melainkan mengubah cara otak kita berinteraksi dengan algoritma tersebut.